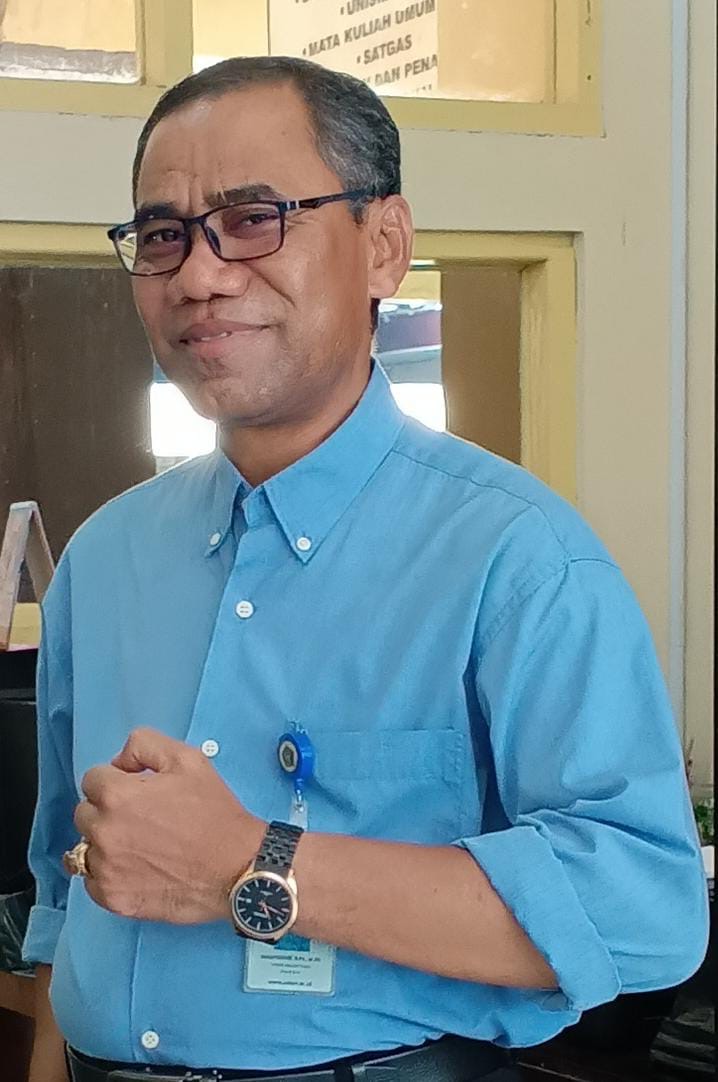Surakarta, Tintabangsa.com- Selama 12 tahun menempuh pendidikan di sekolah, mayoritas siswa di Indonesia terbiasa dengan tuntutan hidup yang serba cepat, target tinggi, dan tekanan ujian yang berkesinambungan. Dari ujian tengah semester, ujian akhir, try out, hingga seleksi perguruan tinggi, semuanya dinilai berdasarkan angka. Fokus pembelajaran bergeser dari pemahaman mendalam menuju upaya untuk bertahan. Dalam sistem ini, belajar kerap terasa seperti beban berat, bukan sebuah proses perjalanan. Tak mengherankan jika banyak siswa yang mengalami kelelahan mental atau academic burnout setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Fenomena gap year pun muncul, bukan karena generasi muda dianggap “manja,” melainkan sebagai cerminan kegagalan sistem pendidikan memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir dan bernapas dalam perjalanan hidup mereka.
Hasil survei Indonesian Youth Wellbeing Survey (2024) yang dirilis oleh UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 4 siswa SMA melaporkan merasa cemas, kehilangan motivasi, atau lelah terhadap rutinitas akademik mereka. Tekanan belajar yang terus diasah tanpa adanya refleksi pribadi menciptakan generasi yang mahir menjawab soal ujian, tetapi bingung ketika dihadapkan dengan pertanyaan mendasar: Aku ingin menjadi apa?
Gap year, yang didefinisikan sebagai masa jeda antara SMA dan perkuliahan, telah menjadi hal yang umum di negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Beberapa universitas bahkan mendorong calon mahasiswa untuk memanfaatkan waktu ini guna mengembangkan diri, misalnya lewat magang, menjadi relawan, atau mengeksplorasi minat pribadi. Namun di Indonesia, gap year sering kali mendapat stigma negatif. Seseorang dianggap gagal, tidak siap bersaing, atau membuang-buang waktu jika tidak melanjutkan pendidikan segera setelah lulus SMA. Padahal, banyak siswa justru menggunakan tahun jeda tersebut untuk mencari arah hidup, memperkuat minat mereka, atau memulihkan kesehatan mental.
Fenomena ini sebenarnya mencerminkan sebuah perlawanan halus terhadap sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada produktivitas dan kecepatan. Di tengah budaya yang menekankan “kuliah cepat, kerja cepat, sukses cepat,” gap year menjadi simbol keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri: Apakah jalur ini benar-benar milik saya, atau sekadar mengikuti arus?
Dari perspektif hukum, gap year juga dapat dianggap sebagai refleksi atas hak tiap warga negara untuk menikmati pendidikan yang bermartabat dan manusiawi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Namun, pemaknaannya tidak boleh menyempit menjadi kewajiban belajar tanpa henti. Pendidikan seharusnya berjalan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, serta kondisi mental individu. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang menimbulkan tekanan berat dan stres malah berisiko melanggar prinsip pendidikan yang sehat. Terlebih jika sekolah tidak dilengkapi dengan psikolog, konselor, atau kebijakan bimbingan karier yang memadai.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan, kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan beban mental berlebih yang dirasakan siswa. Dengan demikian, sistem pendidikan yang terus memaksa siswa berkompetisi tanpa memberikan ruang untuk refleksi dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan struktural. Ditambah lagi dengan ketiadaan bimbingan karier yang komprehensif pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
Sebagian besar sekolah masih mendefinisikan keberhasilan siswa berdasarkan capaian akademik semata, mengabaikan kecenderungan minat dan bakat individu. Akibatnya, tak sedikit siswa memilih jurusan kuliah hanya karena ikut-ikutan teman atau tekanan lingkungan, alih-alih menuruti panggilan hati mereka.
Dalam banyak situasi, keputusan untuk mengambil gap year justru menjadi momen penting bagi individu untuk merebut kembali kendali atas arah hidup mereka. Anak-anak yang sebelumnya bimbang memilih jurusan dapat memanfaatkan waktu jeda ini dengan magang, mengikuti kursus, belajar bahasa asing, atau menekuni minat berwirausaha. Fenomena ini semestinya dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran nonformal yang sejalan dengan prinsip pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa pendidikan mencakup jalur formal, nonformal, dan informal. Oleh karena itu, gap year tetap merupakan ruang belajar asalkan dikelola dengan panduan dan fasilitasi yang tepat.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: apakah kita siap menerima gap year sebagai bagian dari perjalanan pendidikan generasi muda Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini bergantung pada kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mengubah paradigma pendidikan secara mendasar. Sistem pendidikan yang ada perlu bergeser dari orientasi yang hanya mengejar kecepatan dan kompetisi, menuju pendekatan yang lebih reflektif, fleksibel, dan berpusat pada kemanusiaan. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mendukung pergeseran ini meliputi:
- Memberikan kewajiban kepada semua sekolah menengah atas untuk menyediakan layanan konseling karier dan kesehatan mental, bukan hanya untuk siswa dengan masalah khusus tetapi bagi seluruh pelajar yang tengah mencari arah hidup.
- Mengakui nilai pembelajaran nonformal—seperti pengalaman sebagai relawan, magang, atau mengikuti kursus—sebagai bagian penting dalam portofolio pendidikan.
- Mengembangkan program gap year yang difasilitasi langsung oleh pemerintah. Contohnya dapat diambil dari negara seperti Korea Selatan dan Australia, di mana program tersebut memungkinkan siswa berkontribusi secara sosial sambil memperkaya diri mereka sendiri.
- Mendorong universitas agar tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap calon mahasiswa yang mengambil gap year, melainkan melihat pengalaman hidup mereka sebagai aset berharga yang memperkaya proses seleksi.
Kerap kali kita lupa bahwa pendidikan bukanlah perlombaan cepat-cepat meraih gelar, melainkan perjalanan panjang penuh makna. Setiap anak memiliki ritme pertumbuhan masing-masing, dan tidak semuanya siap berlari dalam waktu yang sama. Fenomena gap year seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua bahwa sistem pendidikan nasional perlu memberikan ruang bagi jeda, pemahaman diri, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sudah saatnya berhenti mengukur keberhasilan seorang anak dari kecepatan masuk kuliah dan mulai melihat sejauh mana mereka telah memahami potensi diri serta arah hidupnya. Pada akhirnya, jeda bukanlah tanda berhenti tetapi cara paling bijaksana dan manusiawi untuk memulai kembali, dengan langkah yang lebih matang dan tujuan yang lebih jelas.(TB)
Sumber: Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Slamet Riyadi Surakarta